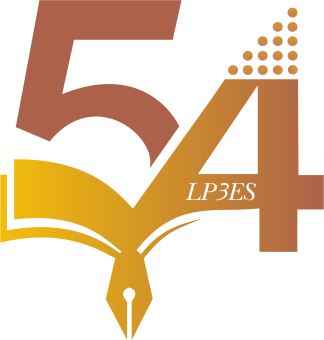Dalam rangka memperingati 27 tahun Reformasi, LP3ES bekerja sama dengan SAFEnet dan YLBHI menyelenggarakan diskusi publik dan media briefing bertema “Membangun Resiliensi Masyarakat Sipil Setelah 27 Tahun Reformasi”. Acara ini bertujuan untuk memetakan ulang posisi dan kekuatan masyarakat sipil Indonesia di tengah penyempitan ruang demokrasi, khususnya di ruang digital. Tiga dekade setelah Reformasi 1998, masyarakat sipil Indonesia kembali menghadapi tantangan serius: semakin menguatnya otoritarianisme, represi terhadap kebebasan berekspresi, serta penyalahgunaan teknologi untuk mengendalikan narasi dan meminggirkan suara-suara kritis, termasuk ketika baru-baru ini tiga orang mahasiswa Universitas Diponegoro mengalami represi ketika menyuarakan pendapat.
Di tengah meningkatnya represi terhadap ruang gerak masyarakat sipil, sekelompok aktivis, akademisi, dan perwakilan organisasi buruh dan mahasiswa berkumpul untuk merefleksikan bagaimana internet telah mengubah lanskap perjuangan sosial di Indonesia. Survey lapangan LP3ES yang menyasar sekitar 1658 organisasi masyarakat sipil (OMS), mengungkapkan bahwa 31% masyarakat sipil mengalami ancaman dan represi dalam berbagai bentuk seperti peretasan, phising, dan intimidasi digital. Terlihat adanya dua pola yang mengemuka, yaitu (1) prevalensi ancaman yang tinggi di wilayah urban dan industrial seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta (2) serangan digital yang muncul di wilayah yang kaya mineral seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, serta Maluku. Kekerasan berbasis gender online juga muncul di ruang digital dan diarahkan kepada OMS dengan provinsi terbanyak yang mengalaminya adalah Sumatera Utara, Jakarta, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Represi kebebasan berekspresi di sosial media juga dilakukan menggunakan UU ITE, umumnya dengan alasan pencemaran nama baik. OMS di wilayah Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur mengalami jumlah kasus terbanyak. Masyarakat sipil perlu menempatkan wilayah-wilayah ini sebagai prioritas untuk advokasi gerakan. Selain itu, survei ini juga mengungkapkan bahwa kesadaran OMS akan hak-hak digital masih tertinggal di beberapa daerah seperti Lampung, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Papua Pegunungan, dan lainnya.
Diskusi yang dilaksanakan di kantor YLBHI ini juga menyoroti bagaimana media sosial menjadi kanal penting dalam proses pengorganisasian massa, terutama ketika ruang fisik dibatasi oleh pandemi. Peristiwa seperti gerakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja menunjukkan kemampuan luar biasa dari masyarakat, terutama mahasiswa dan buruh dalam memanfaatkan platform digital untuk konsolidasi dan mobilisasi secara organik. Serikat buruh bahkan mengalami peningkatan anggota melalui interaksi di media sosial.
Namun, teknologi juga hadir dengan wajah gelapnya. Peserta diskusi mencatat munculnya praktek doxxing, penyalahgunaan UU ITE, serta kriminalisasi terhadap ekspresi digital seperti meme kritik. Kelemahan struktural gerakan digital, seperti kurangnya resiliensi dan potensi disinformasi, mendorong seruan untuk pemetaan kekuatan, musuh, dan kawan dalam ruang digital.
“Media sosial seharusnya bisa menjadi ruang mencerdaskan publik, bukan sekadar arena kontestasi buzzer,” ujar Tasya, salah satu penanggap diskusi.
Zainal Arifin dari YLBHI, menekankan pentingnya memahami perkembangan yurisprudensi terbaru, terutama keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak bisa dipidana. Sayangnya, “praktik baik” ini belum tersebar luas, bahkan di kalangan penegak hukum sendiri.
Diskusi ini juga menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, kesadaran warganet adalah medan baru perlawanan. Untuk itu, dibutuhkan bahasa baru, pendekatan baru, dan konsolidasi yang melampaui sekat-sekat organisasi agar masyarakat sipil tetap mampu menghadapi gelombang otoritarianisme yang semakin lihai memainkan algoritma.