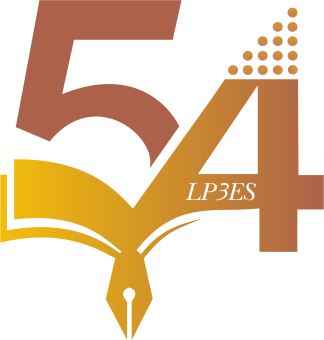LP3ES kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga dan merawat demokrasi Indonesia dengan meluncurkan sebuah buku penting berjudul Pasukan Siber: Operasi Pengaruh dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Buku ini hadir sebagai hasil riset mendalam yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir oleh tim akademisi lintas negara, yang berupaya mengungkap wajah tersembunyi dunia digital Indonesia dalam pasukan siber dan operasi pengaruh yang mereka jalankan.
Acara peluncuran buku tersebut diselenggarakan secara hybrid di Aryaduta Hotel pada Senin (25/8/2025). Turut hadir dalam launching tersebut, Bapak Rahmat Bagja dari Bawaslu, Ibu Betty Idores dari KPU RI, Rektor Universitas Paramadina Prof.Didik J. Rachbini, Pemimpin Redaksi Kompas Bapak Yogi Arif Nugraha, Pemimpin Forum Satu Meja Bapak Budiman Tanuredjo, Ketua Dewan Pers Bapak Komaruddin Hidayat, perwakilan dari Kedutaan Besar Belanda Ibu Shinta serta Bapak Philips J. Vermonte.
Diketahui, beberapa tahun terakhir publik kerap dibuat bertanya-tanya mengenai gelombang percakapan di media sosial yang tiba-tiba muncul, ramai, lalu menggiring opini ke arah tertentu. Banyak yang bertanya, “Siapa yang berada di balik ini semua?” Pertanyaan inilah yang mendorong lahirnya riset panjang yang dituangkan dalam buku ini.
Inspirasi awal pada tahun 2019, ketika gelombang besar penolakan terhadap revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) justru berbalik arah di ruang digital. Saat di jalanan mahasiswa dan masyarakat sipil menolak pelemahan KPK, di dunia maya justru muncul narasi kuat yang mendukung revisi. Lebih jauh, muncul pula tuduhan bahwa KPK disusupi “Taliban”, sebuah label yang sengaja dipakai untuk mendiskreditkan para pegiat antikorupsi. Fenomena ini tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan bagian dari sebuah operasi pengaruh terstruktur, terkoordinasi, dan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu.
Acara peluncuran buku dibuka dengan sambutan dari Fahmi Wibawa, Direktur Eksekutif LP3ES. Dalam pidatonya, Fahmi menegaskan bahwa demokrasi di berbagai belahan dunia tengah mengalami pelemahan, dan Indonesia bukan pengecualian. Ia mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh jika mendapat pengawalan serius, terutama di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali dimanipulasi. “Melalui rezim saat ini, kita perlu memastikan adanya pengawalan terhadap demokrasi. Buku ini hadir untuk membuka mata kita bahwa demokrasi yang sehat hanya mungkin terjaga bila publik memiliki akses informasi yang akurat dan bebas dari manipulasi” ujarnya.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Abd. Hamid, Ketua Dewan Pengurus LP3ES. Hamid menekankan bahwa buku ini adalah cerminan semangat kritis yang telah menjadi DNA LP3ES sejak didirikan. Menurutnya, para pendiri LP3ES selalu menekankan pentingnya sikap kritis terhadap kekuasaan, dan semangat itu kini menemukan relevansinya kembali. Ia mengaitkan fenomena hoaks dengan literatur klasik kitab kuning, yang menyebutkan bahwa berita bohong dapat menimbulkan masalah besar dalam kehidupan masyarakat. “Hoaks bukan hanya sekadar informasi salah, melainkan ancaman serius bagi tatanan sosial dan demokrasi” tegas Hamid.
Diskusi kemudian berlanjut dengan pemaparan dari penulis utama buku Pasukan Siber Wijayanto, Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES & Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro. Ia menyoroti bagaimana media sosial di Indonesia pernah dipenuhi oleh perang tagar pada momentum politik tertentu, salah satunya ketika revisi UU KPK disahkan pada 2019. Dalam waktu singkat, tagar-tagar seperti #KPKdanTaliban, #KPKPatuhAturan, #RevisiUUPKforNKRI, hingga #KPKLebihBaik menjadi viral. Menurut Wijayanto, konten yang beredar saat itu bukanlah produk organik masyarakat biasa, melainkan hasil operasi yang digerakkan secara sistematis. “Pertanyaan yang kami coba jawab lewat buku ini adalah: siapa di balik semua ini? Melalui riset, kami menemukan bahwa ada dua tipe aktor: mereka yang bekerja secara sukarela, dan mereka yang dibayar diam-diam. Yang terakhir inilah yang dikenal dengan istilah pasukan siber” jelasnya.
Penelitian LP3ES dilakukan dengan metode wawancara mendalam kepada 102 anggota pasukan siber, dipadukan dengan analisis big data media sosial. Dari hasil itu, ditemukan bahwa pasukan siber tidak hanya aktif di masa pemilu, melainkan juga dalam mendorong kebijakan, menyerang oposisi, atau bahkan menggiring isu tertentu agar mendominasi ruang publik. Menariknya, latar belakang mereka beragam, namun mayoritas memiliki pengetahuan yang cukup luas, sehingga mampu menyusun narasi yang persuasif.
Dari sisi latar belakang pekerjaan, distribusi informan memperlihatkan variasi yang cukup signifikan. Kelompok terbesar berasal dari kategori Buzzer/Influencer/Agency sebanyak 15 orang, disusul oleh kategori Lain-lain/Belum jelas sebanyak 11 orang, serta pekerja di sektor Pemerintah/ASN/BUMN dan Swasta/Kantoran yang masing-masing berjumlah 8 orang. Selain itu, terdapat pula mereka yang berprofesi sebagai akademisi, aktivis, konsultan, mahasiswa, hingga pedagang dan pelaku usaha kecil. Temuan ini memperlihatkan bahwa pasukan siber tidak berasal dari satu golongan saja, melainkan berakar pada beragam sektor masyarakat.
Dari sisi pendidikan, mayoritas informan memiliki tingkat pendidikan tinggi. Sebanyak 45 orang berlatar belakang pendidikan S1, disusul 26 orang lulusan SMA/SLTA, dan 11 orang lulusan S2. Menariknya, ada juga informan yang berpendidikan hingga S3 berjumlah 4 orang, sementara sebagian lainnya tidak menyebutkan latar pendidikan mereka. Fakta ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pasukan siber memiliki kapasitas intelektual yang cukup memadai untuk menyusun narasi persuasif dalam memengaruhi opini publik. “Keberagaman latar belakang pekerjaan dan tingginya tingkat pendidikan para pasukan siber menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar aktivitas sporadis, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang sistematis” ungkap peneliti LP3ES.
Temuan tersebut diperkuat oleh Peneliti KITLV Leiden, Prof. Ward Barenschot, yang menjelaskan bahwa kerja pasukan siber kini menjadi sumber penghidupan baru. Influencer dan buzzer dibayar oleh koordinator politik atau bisnis untuk menjalankan agenda tertentu. Ward mengidentifikasi adanya empat jenis klien yang memanfaatkan jasa pasukan siber di Indonesia: elit politik, partai politik, aktor yang berhubungan dengan pemerintah, serta kalangan pengusaha. Yang unik dibandingkan negara lain, operasi siber di Indonesia tidak hanya datang dari pihak pro-pemerintah, melainkan juga dari kelompok oposisi.
Ward mengingatkan, keberadaan pasukan siber membawa sejumlah dampak negatif. Pertama, kualitas debat publik merosot karena isu-isu diarahkan sesuai agenda mereka. Kedua, kebebasan berekspresi terancam akibat serangan digital terhadap aktivis atau masyarakat. Ketiga, akuntabilitas demokrasi melemah karena pasukan siber menjual narasi kebijakan pemerintah. Keempat, oligarki semakin menguat karena hanya kalangan elit yang memiliki sumber daya untuk mengoperasikan pasukan siber. Untuk itu, ia menyerukan pentingnya regulasi yang mewajibkan transparansi komunikasi digital, serta perlunya peran media dan perusahaan teknologi dalam membangun ekosistem informasi yang lebih sehat.
Ika Karlina Idris dari Monash Universitas, mengungkapkan bahwa temuan penting dalam buku ini adalah bagaimana media arus utama kerap ikut mengamplifikasi isu viral dari media sosial tanpa verifikasi memadai. “Akibatnya, propaganda digital yang digerakkan oleh buzzer bisa menjalar lebih cepat” ujarnya. Ia mencontohkan, isu-isu strategis seperti perubahan iklim seringkali terabaikan dibandingkan isu politik yang diproduksi secara masif oleh pasukan siber.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat mengaitkan hasil riset ini dengan literatur global, salah satunya The Age of Surveillance Capitalism. Menurutnya, teknologi digital yang beroperasi dalam kerangka kapitalisme justru melahirkan bentuk otoritarianisme baru. “Para diktator modern tidak hanya bersaing, tetapi juga saling berbagi sumber daya demi mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari dominasi partai politik dan oligarki yang mengendalikan media massa,” jelasnya. Ia juga mempertanyakan apakah kedaulatan rakyat masih benar-benar ada, atau justru telah dirampas oleh oligarki.
Sementara itu, Philips J. Vermonte, Presidential Comuunication Ogice menekankan bahwa fenomena rendahnya kepercayaan publik di ruang digital memperparah penyebaran propaganda. Ia menilai, keberadaan ratusan akun yang bisa digantikan dengan multiaccount hanya memperburuk keadaan. “Jika dunia maya dapat dibuat lebih bersih, ia bisa menjadi representasi kerja-kerja sipil. Maka, yang perlu dilakukan adalah mendorong masyarakat kembali pada kerja-kerja analog, memperkuat advokasi kepada perusahaan teknologi agar ikut terlibat, sekaligus mengadvokasi para pengguna” ungkapnya. Philips menambahkan, dari hasil pengamatan PCO, pihaknya tidak menemukan keberadaan buzzer dalam ekosistem mereka.
Diskusi ini ditutup dengan penekanan bahwa buku tersebut bukan sekadar dokumentasi fenomena digital, melainkan juga sebuah peringatan. Wijayanto menegaskan bahwa masyarakat sipil yang kuat dapat menjadi benteng melawan manipulasi digital. Ia mencontohkan resistensi publik yang berhasil menggagalkan upaya memperpanjang masa jabatan presiden. Namun, ia juga mengingatkan bahwa serangan terhadap organisasi masyarakat sipil semakin sering terjadi. “Survei LP3ES menemukan 25 persen organisasi masyarakat sipil pernah mengalami serangan digital, termasuk NGO di Bali yang sebenarnya memiliki kapasitas keamanan digital tinggi” jelasnya.