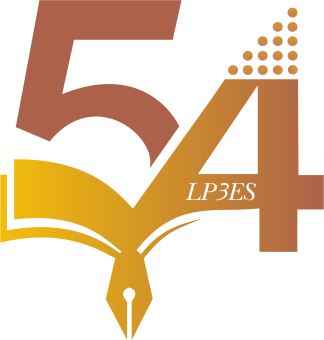Dalam forum diskusi bertajuk “Gerakan Mahasiswa dan Represi Negara”, LP3ES dan Forum Alumni Sekolah Demokrasi LP3ES mengangkat kembali urgensi membahas tekanan terhadap gerakan mahasiswa dan penyempitan ruang sipil di Indonesia. Diskusi ini menghadirkan akademisi, aktivis hak digital, dan praktisi hukum. Moderator acara adalah Ismail Suardi Wekke (The Academia of Papua), dan pembukaan disampaikan oleh Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa. “Saat ini kita merasakan seperti déjà vu,” ujar Fahmi.
“Negara membatasi berbagai macam langkah dan tindakan, membatasi gerak mahasiswa dalam memainkan fungsinya sebagai penjaga moral publik dan kekuatan sipil yang kritis,” ungkapnya. Dalam paparannya, Nukila Evanty (Advisory Board Asia of Centre) mengulas kronologi aksi protes mahasiswa dan buruh yang berlangsung di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Ia menggambarkan situasi yang penuh ketegangan, dengan dugaan keterlibatan polisi yang menyamar dan tindakan represif terhadap massa aksi.
Nukila menjelaskan bahwa represi negara dapat berupa berbagai tindakan yang dilakukan oleh lembaga berwenang terhadap individu atau kelompok dalam wilayah yurisdiksi mereka. Represi ini mencakup pembatasan perilaku dan keyakinan warga negara melalui pengenaan sanksi negatif seperti jam malam, penangkapan massal, dan pelarangan organisasi politik. Selain itu, represi juga dapat berbentuk pelanggaran terhadap integritas pribadi, seperti pengawasan ketat, interogasi, atau penahanan di kantor polisi.
Ia menyebut adanya dugaan keterlibatan polisi yang menyamar dan menyebut bahwa beberapa mahasiswa mengalami kekerasan serta penangkapan: “Ada water cannon selama 20 menit, gas air mata lebih dari satu jam. Dua mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 333 dan 170 KUHP. Media arus utama juga menyudutkan posisi mahasiswa yang ditahan,” tambahnya. Nukila menambahkan bahwa dalam penanganan aksi mahasiswa, aparat harus menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi dan demokratis
“Penegak hukum harus bersikap bijak, tidak reaktif. Gunakan mediasi dan restorative justice. Pemerintah harus memahami pentingnya peran generasi muda dalam promosi HAM,” ungkapnya.
Dalam paparannya, dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menyoroti fenomena penyempitan ruang sipil yang dialami mahasiswa sebagai bagian dari tren global yang juga mengakar kuat di Indonesia. Ia menyebut bahwa situasi ini telah dapat dipetakan sejak 4–5 tahun lalu sebagai bagian dari gejala shrinking civic space, yakni semakin menyempitnya ruang berekspresi warga sipil akibat praktik negara yang represif.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa demokrasi kita telah menjelma menjadi prosedural belaka. Formalitas yang diklaim sebagai demokrasi, padahal substansinya telah kosong.
“Demokrasi kita makin lama makin menyempit. Saya bahkan menyebutnya sebagai gejala fasisme,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bivitri memperkenalkan konsep kompetitif otoritarianisme, sebuah istilah yang merujuk pada negara yang masih menyelenggarakan pemilu dan tampak demokratis secara luar, namun pada dasarnya otoriter. Pemerintah tetap berusaha mempertahankan legitimasi demokratis, tetapi membatasi hak-hak sipil secara sistematis dan menekan oposisi. “Mahasiswa yang menjadi pemohon di MK diteror, bahkan keluarganya juga. Ini bukan yang pertama. Ada rektor yang berharap jadi komisaris. Ketakutan menjadi sistematis dan menular ke mahasiswa. BEM dibekukan, dosen dibungkam,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa kekuasaan saat ini menyajikan demokrasi hanya sebagai citra formal. Bivitri menyoroti intervensi langsung ke institusi pendidikan tinggi: “Ada rektor yang berharap jadi komisaris BUMN. Ketakutan jadi sistemik. Akibatnya, kampus jadi tunduk pada kekuasaan, mahasiswa dibekukan organisasinya, dan dosen takut bicara,” tegasnya.
Dosen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menantang kita untuk melihat kembali perjalanan demokrasi Indonesia. “Pertanyaannya: apakah kita pernah benar-benar melewati masa konsolidasi demokrasi? Jangan-jangan kita hanya sedang berputar-putar dalam masa transisi, atau bahkan kembali ke otoritarianisme,” ungkapnya. Ia menyebut model otoritarianisme saat ini sebagai neo otoritarianisme:
“Zaman Soekarno membubarkan partai. Soeharto menjinakkan lewat dwifungsi ABRI. Pasca reformasi, oposisi dibunuh lewat kasus hukum. Partai oposisi pun dijinakkan,” tambahnya.
Tak hanya partai, aktivisme mahasiswa pun turut ditekan dari dalam:
Tak hanya partai, aktivisme mahasiswa pun turut ditekan dari dalam“Pascareformasi, mahasiswa kerap dipukul dari dalam, dibenturkan dengan sesama mahasiswa. Ini mulai sejak SBY, puncaknya di Jokowi, dan berlanjut di era Prabowo,” tegasnya
Zainal juga menyoroti manipulasi ruang publik: “Negara seolah membuka ruang publik, tapi itu satu arah. Sejarah dibangun sebagai mitos. Negara menentukan siapa yang jadi pahlawan, siapa yang jadi penjahat,” tambahnya. Ia menutup dengan catatan penting: “Yang bisa membuka ruang publik adalah oposisi. Jika tidak ada oposisi, tidak ada ruang diskursus. Tanpa itu, demokrasi hanya ilusi,” ujarnya.
Dalam paparannya, Hafizh Nabiyyin dari SAFEnet menegaskan bahwa represi negara terhadap mahasiswa kini tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga digital. Ia menyebut mahasiswa sebagai kelompok paling rentan. “Situasi di Indonesia, SAFEnet mencatat bahwa pelajar, mahasiswa, OMS, dan aktivis menjadi paling rentan mengalami represi digital antara Januari hingga Maret 2025,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bentuk serangan digital yang dialami mahasiswa terbagi dalam dua kategori besar. “Serangan teknis seperti peretasan, DDoS, Zoom Bombing, hingga phishing. Sementara serangan psikologis berupa kriminalisasi, doxing, pengancaman, impersonasi, NCII, hingga serangan buzzer dan trolling,” jelasnya
Hafizh mendorong peningkatan kapasitas hukum dan keamanan digital secara kolektif. “Adakan pelatihan keamanan digital internal, bangun kolektif CSIRT di kampus atau kota, kurangi ketergantungan pada Big Tech, dan gunakan software open source,” tegasnya. “Bangun kesadaran bahwa Big Tech adalah korporasi, bukan filantropi,” tambahnya.